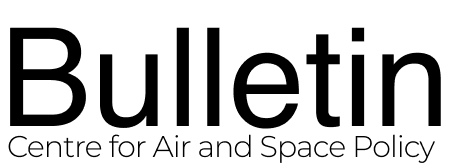RUU Pengelolaan Ruang Udara: Apa Yang Dipertaruhkan Di Pasal 8 Ayat 2 Huruf (a)?

Pemerintah telah menetapkan RUU Pengelolaan Ruang Udara (RUU PRU) masuk ke dalam Prolegnas pembahasan di DPR untuk diproses menjadi Undang-Undang. Lahir dari usulan Kementrian Pertahanan RI, RUU ini banyak ‘melahirkan’ sebuah prinsip hukum yang tidak umum yang berlaku dalam ketentuan hukum internasional. Pendefinisian wilayah ruang udara berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat 2 huruf (a) dari RUU yakni ‘ruang udara internasional di atas wilayah yurisdiksi Indonesia’, melahirkan pertanyaan utama dalam hukum udara dan kaitannya menurut UNCLOS 1982 terkait zonasi wilayah laut, mengingat RUU ini dalam pembukaan ‘menimbangnya’ memasukkan ketentuan dalam UNCLOS 1982 sebagai pertimbangan.

Ruang Udara Menurut Konvensi Chicago
Perdebatan sifat dan karakteristik ruang udara suatu negara di saat pembentukan Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional yang menggantikan Konvensi Paris 1919 melahirkan dua kutub utama antara Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa. Kutub negara-negara Eropa menginginkan kedaulatan penuh atas ruang udara suatu negara seperti termaktub dalam Konvensi Paris 1919 harus dipertahankan, di saat yang sama Amerika Serikat menginginkan adanya kebebasan lalu lintas udara untuk mendorong akses pasar global perpindahan orang dan manusia yang lebih luas.
Dua kutub ini kemudian menghasilkan sebuah kompromi dalam Konvensi Chicago 1944 yang tetap mempertahankan prinsip kedulatan penuh atas ruang udara suatu negara seperti yang termuat dalam Pasal 1 dari Konvensi. Namun, dipertahankannya prinsip ini diikuti dengan pengakuan akan kebebasan lalu lintas udara yang bersifat lebih fleksibel atau dengan istilah sovereignty is absolute, but access is negotiable. Istilah ini kemudian merubah paradigma di Konvensi Paris 1919 menjadi lebih memungkin bagi negara-negara untuk melakukan sebuah kesepakatan untuk lalu lintas udara baik secara bilateral maupun multilateral. Kesepakatan ini mengatur terkait hal-hal jenis lalu lintas udara yang dibolehkan oleh negara yang dilintasi ataupun negara didarati atau dikenal sebagai perjanjian pertukaran freedom of the air.
Berlanjut pada ketentuan di Pasal 2 dari Konvensi Chicago 1944, semua negara bahkan negara-negara maritim dalam hal pembentukan Konvensi ini sepakat bahwa luas secara horizontal atau lateral suatu negara sebatas luas wilayah daratnya ditambah dengan laut territorial suatu negara. Artinya tidak ada perbedaan yang muncul di antara negara-negara dari prinsip ini, mengingat lalu lintas penerbangan internasional tidak boleh dikekang. Konvensi Chicago 1944 bahkan dalam perkembangannya hingga saat ini tidak pernah menambahkan area zonasi ruang udara di luar ruang udara nasional dan ruang udara internasional di luar ketentuan Pasal 2 Konvensi Chicago 1944.
Zonasi Wilayah Berdasarkan UNCLOS 1982
Dalam konteks hukum laut, wilayah laut sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh UNCLOS 1982 membagi zonasi laut menjadi beberapa zona yang terdiri atas: (i) perairan pedalaman; (ii) laut teritorial; (iii) zona tambahan/contiguous zone; (iv) zona ekonomi eksklusif (ZEE); (v) landas kontinen; (vi) laut bebas/high sea; dan (vii) area. Pembagian zona ini umumnya memberikan perbedaan terkait hak dan kewajiban bagi negara-negara pantai, maupun negara pelintas terkait banyak hal seperti yurisdiksi, pengelolaan sumber daya alam hingga kebebasan dalam melakukan pelayaran.
Mengacu pada isu RUU PRU yang sedang dibahas di DPR saat ini, perancang RUU ini menggunakan dua analogi zonasi di laut yang kemudian diterapkan, yaitu zonasi laut territorial dan ZEE. Pasal 2 dan 3 dari UNCLOS 1982 menetapkan luar laut territorial suatu negara adalah sejauh 12 mil laut dari garis pangkal. Konsekuensinya, di wilayah ini, negara hingga 12 mil laut memiliki kedaulatan penuh atas perairan, dasar laut hingga ruang udara di atasnya. Lebih lanjut, negara di wilayah kedaulatannya dapat menerapkan yurisdiksi hukumnya secara penuh.
Selanjutnya yaitu ZEE. Seperti yang diatur di Pasal 55 – 75 UNCLOS 1982, zona ini terletak 188 mil laut ditarik dari zona laut territorial suatu negara. Zona ini sekalipun bukan merupakan bagian dari wilayah teritorial negara pantai, namun zona ini memberikan ‘hak berdaulat’ yang terbatas bagi negara pantai dalam hal eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam laut. Sehingga negara pantai di ZEE memiliki ‘yurisdiksi terbatas’ sekalipun bukan yurisdiksi penuh layaknya laut teritorial. Oleh karenanya, di zona ini, setiap kapal asing yang bukan kapal berbendera negara pantai dari ZEE, tetap memiliki hak dalam hukum laut internasional untuk melakukan pelayaran atau kebebasan navigasi.
Rumitnya pembagian zonasi di laut memang tidak sesederhana pembagian zonasi di ruang udara yang hanya membagi ruang udara menjadi dua, yaitu ruang udara negara dan ruang udara internasional. Hal ini tak lepas dari potensi keuntungan dalam hal pengelolaan sumber kekayaan alam yang berada di dalam maupun dasar laut hingga di bawah dasar laut. Dari pembahasan pembanding di atas antara rezim hukum udara dan hukum laut dalam membagi zonasi ruang udara dan laut, penulis berkeyakinan bahwa kemunculan istilah baru dalam RUU PRU yang sedang menjadi pembahasan di DPR yakni ‘ruang udara internasional di atas wilayah yurisdiksi Indonesia’ mengambil dari pembagian zonasi yang berada di laut. Tentu hal ini adalah sebuah pertanyaan besar terkait sumber hukum apa yang diambil dari pembentuk RUU ini yang secara prinsip umum mengatur ketentuan di ruang udara namun prinsip yang terdapat dalam hukum udara internasional sangat bertentangan dan tidak berdasar. Kemunculan istilah ini dalam hal pengelolaan ruang udara, seperti menarik Indonesia jauh ke belakang atau bahkan ke era kegelapan pengetahuan perkembangan hukum udara global yang berkembang dan diimplementasikan saat ini. Ketidakmampuan pembentuk RUU ini dalam membedakan rezim hukum udara dan hukum laut dalam merancang UU sangat kuat diduga sebagai kesalahan fatal dalam menafsirkan istilah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seperti yang diatur dalam UNCLOS 1982. Pembentuk RUU ini seolah ingin mengatur ruang udara nasional layaknya mengatur lautan dengan yurisdiksi tambahan berupa ‘hak berdaulat’, yang tentu secara karakteristik memiliki perbedaan mendasar baik secara sifat, ruang maupun potensi kekayaan alam. Dampaknya, Indonesia berpotensi akan mengalami kesulitan dalam menghadapi audit dari International Civil Aviation Organization (ICAO) terkait ketersesuaian aturan nasionalnya dengan ketentuan penerbangan internasional.
***
Adhy Riadhy Arafah is Deputy Director of Centre for Air and Space Policy (CASP); Lecturer at Faculty of Law, Universitas Airlangga; Guest Lecturer at Surabaya Aviation Polytechnic; Former Director of Airlangga Institute of International Law Studies (AIILS), Faculty of Law Universitas Airlangga; Former Director of Centre for Air and Space Law (CASL), Faculty of Law Universitas Airlangga; various former guest lecturers at Aviation School of Training Centre, Indonesian Ministry of Transportation in Papua and Palembang; Former Guest Lecturer at Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surabaya.